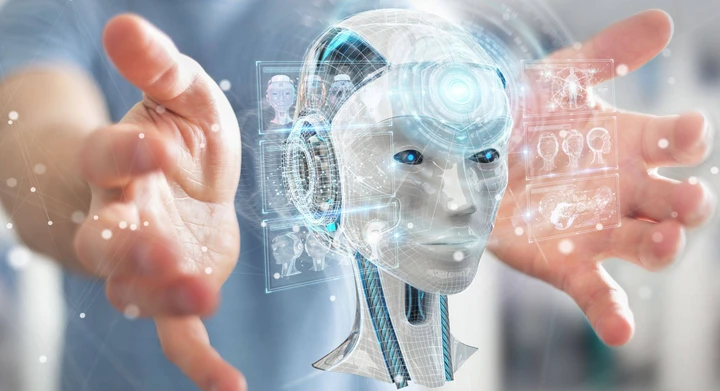Kita hidup di siklus yang gila. Teknologi baru muncul, kita puja-puja, buat karya dengannya, lalu dia usang. Berganti. Lalu kita puja-puja lagi yang baru. Rasanya kayak treadmill yang muter terus. Tapi ada sekelompok seniman di 2025 ini yang nggak mau ikut lari. Mereka malah sengaja turun dari treadmill itu. Dan duduk di pinggirnya. Dengan sengaja mereka pilih alat yang udah tahu akan mati. Kenapa? Ini bukan nostalgia. Ini perlawanan.
Ini adalah gerakan seniman yang melihat obsolesensi — kedaluwarsa teknologi — bukan sebagai musuh, tapi sebagai bahan baku. Sebagai batas waktu yang justru memberi makna. Mereka nggak takut karya mereka nggak bisa diakses nanti. Itu justru poinnya.
Melawan Virus dengan Menjadi Virus
Logika industri kreatif digital selalu mengejar yang future-proof. Tapi gerakan ini percaya, usaha untuk future-proof itulah virusnya. Dia bikin kita selalu gelisah, selalu ngejar, dan akhirnya karya cuma jadi produk dari tools terbaru. Seni sebagai antibodi bekerja sebaliknya: dia sengaja masukin kode kedaluwarsa ke dalam DNA karyanya.
- Studi Kasus 1: Karya AR yang Hanya Bisa Dibuka di iPhone 15 Pro. Bayangin sebuah instalasi seni digital berupa patung virtual AR yang tersebar di sudut kota. Tapi dia hanya bisa diakses dengan aplikasi khusus yang dirancang hanya untuk chip A17 Pro di iPhone 15 Pro. Tidak untuk model berikutnya. Sang seniman, Maya, bilang: “Saya ingin mengunci pengalaman itu pada momen spesifik dalam sejarah teknologi. Ketika perangkat ini jadi relik, karyanya ikut jadi memori yang hanya hidup dalam ingatan dan dokumentasi.” Ini adalah pembatasan yang diangkat jadi konsep. Menurut arsip New Media Archive, 2024 adalah tahun pertama di mana lebih dari 60% karya pemenang festival seni media baru menyertakan elemen kedaluwarsa terencana dalam proposal konseptualnya.
- Studi Kasus 2: Novel Interaktif yang Server-nya Akan Dimatikan. Ada sekelompok penulis dan programmer yang bikin cerita game online masif. Plotnya bergantung pada interaksi pemain. Tapi di Terms of Service-nya, jelas tertulis: “Server akan ditutup dan semua data dunia akan dihapus permanen pada 31 Desember 2029.” Deadline itu jadi bagian dari narasi. Komunitas pemain jadi punya misi bersama: mencapai akhir cerita sebelum ‘kiamat digital’ mereka. Teknologi di sini bukan medium abadi, tapi panggung sementara yang dramatis.
- Studi Kasus 3: Sculpture dengan Microcontroller yang Diprogram untuk Rusak. Sebuah patung fisik yang indah, tapi di dalamnya ada chip sederhana yang mengontrol elemen cahaya kecil. Chip itu diprogram dengan sengaja agar memorinya mengalami bit rot — kerusakan data — dalam pola acak selama 5 tahun. Perlahan, pola cahayanya berubah, jadi kacau, dan akhirnya padam selamanya. Karyanya berevolusi menuju kematian. Sang seniman tidak menyembunyikan ini. Malah dipamerkan sebagai bagian dari judul: “*Elegi untuk Sebuah Siklus, 2025-2030*”.
Gimana Kalau Lo Mau Coba Bikin Karya ‘Fana’ Seperti Ini?
- Pilih Medium yang Lo Tahu Siklus Hidupnya. Jangan asal. Pilih teknologi yang lo paham betul kira-kira kapan dia akan mulai ditinggalkan. Misal, generative AI yang based pada model tertentu, platform sosial yang lagi tren tapi volatil, atau kode tertentu yang bergantung pada library yang udah nggak didukung.
- Jadikan ‘Masa Hidup’ sebagai Bagian dari Judul dan Pernyataan Konsep. Jangan sembunyiin. Tulis jelas: “Karya ini dirancang untuk mengalami degradasi dan menjadi tidak dapat diakses setelah [tanggal].” Itu akan memfilter penikmatnya. Hanya mereka yang rela menerima pembatasan ini yang akan benar-benar menghargai.
- Dokumentasikan Proses ‘Penuaan’-nya. Ini penting. Buat karya itu bukan tentang akhir yang hilang, tapi tentang proses menuju akhir. Rekam perubahan-perubahannya. Buat diarium visual atau blog. Dokumentasi itu akan jadi artefak sekunder yang justru mungkin lebih abadi.
- Bekerjasama dengan Komunitas yang Paham. Cari kolektif atau forum seniman digital yang punya minat serupa. Berbagi sumber daya, hosting, atau pengetahuan teknis tentang bagaimana merancang ‘kegagalan’ yang elegan dan bermakna.
Jebakan yang Bisa Bikin Konsepnya Jadi Kosong atau Cuma Gimmick
- Hanya Mengejar Sensasi “Akan Hilang”. Kalau karyanya sendiri payah, konsep kedaluwarsanya cuma jadi alesan buat menutupi itu. “Ini memang jelek, soalnya nanti juga ilang.” Bukan begitu. Karyanya harus kuat dulu, baru elemen kedaluwarsa terencana-nya akan memberi kedalaman.
- Tidak Siap Melepas dan Benar-benar Membiarkannya Hilang. Ini ujian sebenarnya. Ketika waktunya tiba, lo harus tega matiin server, hapus file master, atau biarkan hardwarenya rusak. Kalau lo backup diam-diam atau bikin versi baru, seluruh konsepnya jadi bohong. Seni sebagai antibodi butuh komitmen total.
- Mengabaikan Aspek Lingkungan (E-Waste). Hati-hati dengan karya fisik yang nantinya jadi sampel elektronik. Rencanakan daur ulang atau “pemakaman” yang bertanggung jawab untuk komponennya. Jangan sampai perlawanan pada obsolesensi malah berkontribusi pada sampah.
- Terlalu Narsis dan Tidak Mempertimbangkan Penikmat. Karya lo “mati” dalam 5 tahun, oke. Tapi apa penikmat punya cukup waktu untuk mengalami, memahami, dan meresapi? Atau cuma jadi aksi ego lo sendiri? Beri ruang yang cukup untuk interaksi yang berarti sebelum akhir tiba.
Kesimpulan: Keabadian yang Lebih Besar Ada dalam Penerimaan akan Kefanaan
Gerakan seniman ini pada dasarnya mengajak kita berpikir ulang. Selama ini kita berjuang mati-matian melawan obsolesensi teknologi, seolah itu adalah kekalahan. Tapi bagaimana jika kita justru merangkulnya? Menjadikan siklus hidup yang pendek itu sebagai tema, sebagai rhythm, sebagai bagian dari keindahan itu sendiri.
Dengan sengaja memasang pembatasan waktu pada teknologi, mereka menciptakan seni yang hidup dengan lebih intens. Yang menantang kita untuk hadir sepenuhnya sekarang, karena besok karyanya mungkin sudah berbeda, atau bahkan hilang.
Ini adalah cara yang radikal untuk mengatakan: nilai sebuah karya tidak terletak pada kemampuannya bertahan selamanya di cloud, tapi pada bekas yang ditinggalkannya dalam ingatan dan percakapan kita. Bekas yang justru mungkin lebih permanen daripada file digital mana pun.
Jadi, teknologi apa yang akan kamu pilih untuk ‘dikubur’ bersama karyamu?